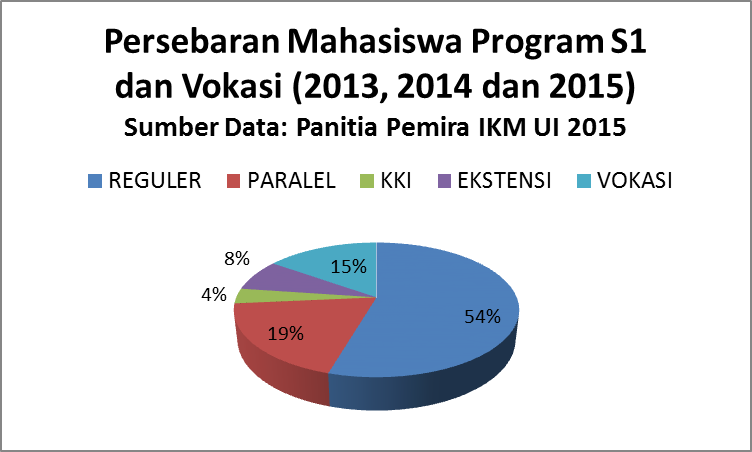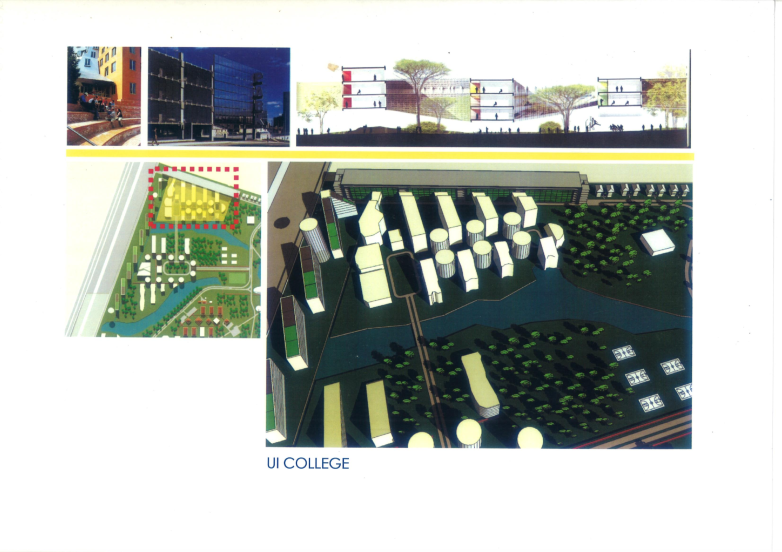Pemerintahan yang demokratis memiliki peluang sekaligus tantangan untuk memaksimalkan integrasi nasional. Secara alami demokrasi juga memiliki kondisi tertentu mengenai identifikasi ‘kami’ dan ‘kalian’ atau kawan dan lawan. Menurut Chantal Mouffe, mengidamkan demokrasi tanpa adanya ‘lawan’ merupakan hal yang berbahaya, sebab kondisi tersebut justru akan melemahkan demokrasi dan memperkuat pemerintahan yang otoriter.[1] Konteks pandangan Mouffe tersebut berbicara mengenai dilema di dalam demokrasi ketika sebuah kelompok masyarakat ingin membentuk subordinasi terhadap kelompok lainnya, padahal kelompok tersebut harusnya dipertahankan.
Dilema Mouffe mengenai paradoks dalam demokrasi menjadi relevan untuk didiskusikan pada konteks keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia belakangan ini. Tulisan ini akan mendiskusikan mengenai tantangan keberagaman bangsa Indonesia, terutama setelah munculnya isu primordial pada Aksi Bela Islam yang begitu dominan dipertontonkan di berbagai media. Sebagai muatan opini, tulisan ini ingin menjawab pertanyaan “bagaimana seharusnya keberagaman bangsa Indonesia menyikapi menguatnya kelompok masyarakat yang eksklusif di Indonesia?”
Sejalan dengan konsep Strategi Nasional Wawasan Kebangsaan yang disusun oleh Bappenas, seharusnya Pancasila dapat menjadi landasan utama bagi penyamaan pemahaman mengenai toleransi antar umat beragama, perlindungan HAM, aktualisasi nilai budaya lokal dan nasional, pemantapan demokrasi, dan keadilan ekonomi.[2] Tulisan ini akan dibagi menjadi tiga pembahasan: integrasi kebangsaan era orde baru, integrasi kebangsaan era reformasi dan tantangan integrasi kebangsaan dan konsolidasi demokrasi.
Orde Baru
Pada umumnya sosiolog menggunakan pendekatan normatif, fungsional dan koersif untuk melihat pola dan strategi integrasi yang diterapkan di tiap lapisan masyarakat. Paulus Wirutomo, guru besar sosiologi Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa setiap negara pasti memiliki salah satu dari ketiga pola integrasi tersebut. Integrasi normatif terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama atau adanya solidaritas. Seiring semakin kompleksnya tatanan masyarakat, mengutip Emile Durkheim, Wirutomo menjelaskan bahwa ketergantungan antar masyarakat akan menjadi semakin fungsional. Sedangkan pada integrasi fungsional, masyarakat berintegrasi karena telah terbentuk suatu sistem kemasyarakatan yang telah saling berkait antar unsurnya. Syarat dari integrasi fungsional adalah pemerataan fungsi dari tiap-tiap unsur yang saling berkaitan dan memiliki kegunaan. Jika terjadi ketimpangan fungsional karena didominasi oleh unsur masyarakat tertentu, maka bisa jadi integrasi fungsional tidak tercipta. Kemudian integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk karena adanya kekuasaan yang lebih besar yang dapat bersifat memaksa dengan menggunakan berbagai institusi sosial.[3]
Integrasi kebangsaan di era orde baru, pemerintahan Suharto tahun 1965 hingga 1998 dinilai menggunakan pendekatan koersif. Ketika itu pemerintah menekan budaya dan identitas tertentu untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat pada umumnya. Salah satu contohnya adalah diwajibkannya perubahan nama dan penggunaan bahasa bagi etnis Tionghoa sesuai dengan nama yang umum digunakan di Indonesia. Wirutomo mengistilahkan fenomena tersebut sebagai jawanisasi.[4] Jawanisasi adalah kondisi ketika kebudayaan yang dominan di Indonesia menggantikan kebudayaan dan identitas lainnya. Pemerintahan orde baru tidak segan untuk menggunakan aparatnya untuk melancarkan doktrin persatuan baik dengan kekerasan, maupun institusi kemasyarakatan seperti pendidikan, media massa dan lain sebagainya.
Lucia R. Kusumadewi menjelaskan bahwa era kepemimpinan Suharto dimulai dengan tragedi pembunuhan 6 jendral disusul pembunuhan massal terhadap individu dan kelompok yang dinilai memiliki paham dan afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Semenjak itu PKI dan komunisme dicap sebagai paham dan kelompok terlarang. Korban pembunuhan tidak hanya jatuh dari pihak yang dituduh sebagai PKI dan komunis, sebab militer merangkul berbagai kelompok agama seperti Nahdatul Ulama (NU) untuk menumpas sisa-sisa PKI dan komunisme. Akibatnya diperkirakan hingga dua juta penduduk muslim di Jawa Timur berpindah agama untuk menyelamatkan diri dari konflik horizontal.[5]
Sebagai jendral militer yang memimpin penumpasan PKI dan komunisme, Suharto mendaulat dirinya sebagai pimpinan negara dan memperkuat poros pendukungnya dengan mendirikan Golongan Karya (Golkar). Tidak hanya itu, pada tahun 1973 pemerintah mengeluarkan aturan bahwa hanya diperbolehkan satu partai berlandaskan agama, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).[6] Hal ini mengakibatkan hanya terdapat dua partai (Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan) dan satu organisasi yang awalnya enggan disebut partai oleh Suharto, yakni Golkar.
Menurut Kusumadewi, orde baru mengikuti pembagian karakteristik Islam yang dipetakan oleh C. Snouck Hurgonje, yakni Islam agama atau Islam kultural dan Islam politik. Melalui pemetaan tersebut, Suharto meningkatkan aktivitas Islam agama atau kultural dan menekan Islam politik. Selain melaksanakan depolitisasi, orde baru juga menjalankan ‘politik pengabaian’ untuk mengurangi kelompok aliran yang muncul serta kepercayaan lokal. Secara kongkret, sejak tahun 1978, orde baru melaksanakan pengawasan aliran melalui Pengawas Aliran-aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Tercatat sekitar 517 aliran kepercayaan lenyap antara tahun 1949 hingga tahun 1992.[7]
Pada dasarnya orde baru telah secara sistematis meredam menguatnya identifikasi kawan dan lawan yang sangat wajar muncul dalam rezim yang demokratis. Berbagai paham persatuan ditanamkan melalui indoktrinasi, salah satunya dengan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Melalui P4 dan berbagai program indoktrinasi orde baru lainnya, Pancasila justru dijadikan sebagai alat melanggengkan kekuasaan dan menekan kritik. Sangat rawan bagi kelompok di luar pemerintahan yang mengkritik presiden ketika itu dilabeli sebagai ‘subversif’, ‘Organisasi Tanpa Bentuk’, ‘anti-Pancasila’ atau ‘tidak Pancasila-is’.
Orde baru dan Suharto tidak hanya diingat karena lama periodenya, namun salah satunya juga disebabkan oleh diutamakannya sektor ekonomi sebagai ‘panglima pembangunan’ dibandingkan sektor politik. Sehingga selain penyederhanaan partai, berbagai kelompok organisasi masyarakat era orde baru begitu terbatas melaksanakan kegiatannya. Integrasi koersif era orde baru terbukti dengan efektif menekan konflik horizontal. Meskipun sejak tahun 1990-an terdapat beberapa konflik yang terjadi, namun konflik tersebut tidak meluas, karena penyebaran informasi melalui media massa juga dikendalikan dengan ketat oleh orde baru. Integrasi koersif oleh orde baru melalui indoktrinasi, peleburan partai dan berbagai ‘politik pengabaian’ terhadap kelompok masyarakat dan aliran kepercayaan menjadi catatan penting pada perkembangan kebangsaan Indonesia. Setelah Suharto lengser pada 1998, praktik integrasi koersif ditolak dan diubah oleh berbagai lapisan masyarakat. Era reformasi yang telah diakui oleh berbagai ilmuan politik sebagai demokratisasi Indonesia menandai tanggung jawab bangsa untuk dapat membangun integrasi normatif dan integrasi fungsional pada skala nasional.
Reformasi
Pada konteks kebangsaan, setelah lengsernya orde baru, banyak muncul konflik seperti akumulasi dari lebih 30 tahun kemarahan yang tertahan. Etnis keturunan Tionghoa banyak menjadi korban harta dan jiwa. Beberapa konflik berbau SARA juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Gerry van Klinken berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi selama periode transisi bersifat politik namun tidak memiliki hubungan langsung. Pemicu dan pelaku konflik menurut van Klinken bukanlah kelas menengah ataupun kelompok aktivis yang melengserkan orde baru, akan tetapi orang yang mengklaim didukung oleh latar belakang etnis dan agama tertentu.[8] Meski demikian van Klinken kesulitan untuk membuktikan bahwa konflik komunal yang terjadi didorong oleh kelompok politik tertentu.
van Klinken berpendapat bahwa latar belakang etnis bukanlah hal utama yang menyebabkan munculnya konflik komunal di berbagai daerah, seperti di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Poso dan Ambon. Melandaskan analisanya pada sensus tahun 2000, menurut van Klinken sensus tersebut pertama kalinya penduduk ditanyakan mengenai latar belakang suku dan etnisnya, setelah 70 tahun tidak didata. Hasilnya ia menyimpulkan bahwa korelasinya sangat lemah antara tingkat keberagaman dengan konflik yang terjadi. Akhirnya van Klinken berpendapat bahwa mayoritas kerusuhan yang terjadi disebabkan oleh kemarahan masyarakat terhadap orde baru yang dilampiaskan tanpa arah. Bentuk kemarahan tersebut disebut oleh van Klinken sebagai kekerasan yang irasional.[9]
Pendapat van Klinken mungkin kurang bisa diterima untuk digeneralisasi ke seluruh Indonesia. Salah satu contohnya, resolusi konflik di Ambon sendiri pada akhirnya mendamaikan kerusuhan antar umat beragama, yakni Islam dan Kristen, dengan sumpah kebudayaan yang disebut pella dan gandong. Pella adalah sebuah perjanjian yang dibuat antar desa, kampung atau wilayah untuk menghidupkan rasa senasib sepenanggungan. Sedangkan gandong adalah sebuah pengingat bahwa suatu kelompok masyarakat tertentu memiliki garis keturunan yang sama. Alhasil dengan Pella Gandong tersebut konflik di Ambon, Maluku, dapat berakhir dan umat beragama dapat rukun hingga kini.
Setelah Suharto mengundurkan diri, segera BJ Habibie menjabat sebagai Presiden. Selama kurang lebih setahun kepemimpinannya, Habibie membuka lebar-lebar keran demokratisasi dan desentralisasi, yang tentu sejalan dengan dorongan reformasi 1998. Pada konteks desentralisasi, salah satu hal yang paling diingat hingga kini adalah dilaksanakannya referendum bagi Timor Timur yang berujung pada terpisahnya wilayah tersebut dari Republik Indonesia. Pada demokratisasi, Presiden Habibie melepaskan tahanan politik, menghapus sensor media massa, mencekal pelanggar HAM dan koruptor, dan yang paling penting adalah mempersiapkan pemilihan presiden berikutnya.
Robert W. Hefner menyebut pemilihan presiden pasca reformasi sebagai ‘The Great Hope’. Hefner menyoroti bahwa setelah reformasi, wacana mengenai negara Islam muncul kembali, akan tetapi dukungan terhadap kelompok konservatif Islam pada tahun 1999 jauh menurun dibandingkan tahun 1955. Jika pada tahun 1955 dukungan terhadap partai Islam sebesar 44%, pada tahun 1999 hanya sebesar 16%.[10] Pemilihan Presiden pada tahun 1999 yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tidak terlepas dari isu agama dan golongan. Menurut catatan Hefner, ketika itu Abdurrahman Wahid didukung oleh kelompok Islamis yang beranggapan Megawati Sukarno Putri sebagai sosok yang sekuler.[11] Presiden Abdurrahman Wahid sendiri akhirnya memimpin hampir selama 2 tahun, sejak 20 Oktober 1999 hingga dituntut untuk mengundurkan diri pada 23 Juli 2001 karena berbagai kebijakannya. Alhasil Megawati Sukarno Putri diambil sumpahnya untuk menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian beliau menjabat sebagai Presiden sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.
Uncivil Society & Bad Civil Society
Kembali pada pembuka tulisan ini, bahwa demokrasi di Indonesia tengah mengalami paradoks setelah berhasil keluar dari rezim yang otoriter. Sejak awal pembentukan institusi yang demokratis telah muncul kelompok masyarakat yang menonjolkan aspek tidak demokratis. Baik yang menggunakan kekerasan ataupun bentuk diskriminasi lain dalam metode kelompoknya. Hefmer menggunakan istilah Uncivil Society terhadap Front Pembela Islam (FPI), Laskar Mujahidin dan Laskar Jihad. Sedangkan Simone Chambers dan Jeffrey Kopstein secara khusus menulis jurnal mengenai “Bad Civil Society” sebagai argumentasi betapa berbahayanya kelompok sipil yang anti demokrasi, walaupun pada negara demokrasi yang paling stabil sekalipun.[12]
Secara eksplisit Hefner menyebut terdapat elit-elit yang turut berkontribusi bagi terbentuknya FPI pada 17 Agustus 1998. Ketika reformasi pendiri FPI yang telah memiliki pengikut sebelumnya, diminta untuk membantu melindungi MPR RI bersama Pam Swakarsa oleh elit terkait. Selain itu pada tahun 2001, FPI juga membantu Golkar untuk memberangus toko-toko buku yang masih menjual buku yang bermuatan komunisme dan sosialisme. Akan tetapi menurut Hefner FPI punya tujuan sendiri. Yakni tindak main hakim sendiri atas berbagai dalih penegakan syariat Islam, baik penutupan paksa rumah ibadah, penutupan diskotek, pelarangan minuman keras, dan lain sebagainya.[13]
Mark Woodward, M. Yahya, I. Rohmaniyah, C. Lundry, dan A. Amin berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh FPI telah dapat didefinisikan sebagai terorisme. Mereka mengacu pada definisi militer Amerika yakni:
“the calculated use of unlawful violence or threat of unlawful violence to inculcate fear, inteded to coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goals are generally political, religious, or ideological”[14]
FPI bergerak dengan landasan menegakkan syariat Islam. Tentu syariat Islam di Indonesia mengacu pada berbagai fatwa atau pendapat keagamaan yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akan tetapi selain karena fatwa dan pendapat keagamaan MUI merupakan sebuah himbauan yang patut untuk diimani secara independen oleh umat beragama Islam di Indonesia, FPI tidaklah memiliki hak di mata hukum untuk bertindak secara sewenang-wenang. Secara garis besar yang membuat diskursus mengenai FPI tidak dianggap sebagai kelompok teror adalah karena FPI atau organisasi serupa menggunakan fatwa MUI sebagai landasan kegiatan diskriminatifnya. Woodward et. al menyimpulkan bahwa ada dua kemungkinan kenapa organisasi seperti FPI dapat bertahan, yakni karena pemerintah terlalu lemah untuk membendung FPI atau tidak adanya political will untuk menghadapi FPI.[15]
Kelompok sipil seharusnya bahu membahu memperkuat konsolidasi demokrasi sesuai dengan kepentingannya. Seperti halnya LSM, organisasi serikat buruh dan lain sebagainya yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang eksklusif, namun juga bagi kepentingan publik. Secara tegas Andi Rahman Alamsyah menyatakan mereka yang tidak turut mempromosikan inklusivitas, toleransi, anti kekerasan dan diskriminasi, serta adab bermasyarakat adalah bad civil society.[16]
Kembali pada konsep yang dipaparkan oleh Chambers dan Kopstein, negara turut memelihara bad civil society ketika terjadi keadaban yang partikular (particularist civility). Chambers dan Kopstein yakin bahwa bad civil society dapat tumbuh subur pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Akan tetapi hal tersebut tidak terlalu berpengaruh apabila isu yang dipermasalahkan berkaitan dengan kepentingan eksklusif, bukan kepentingan publik. Berkaitan dengan paradoks dalam demokrasi, kebebasan berkumpul dan berserikat (freedom of association) tidak jarang juga digunakan oleh bad civil society untuk mempertahankan dirinya di kala terancam.[17]
Integrasi Kebangsaan dan Konsolidasi Demokrasi
Menyikapi keberagaman bangsa Indonesia dengan berbagai latar belakang etnis, agama, bahasa dan lain sebagainya, seharusnya masyarakat bisa memiliki visi mengonsolidasikan diri sesuai Pancasila dan konstitusi, UUD 1945. Mouffe berpendapat bahwa pada kondisi alami demokrasi yang mencakup kawan dan lawan, serta pertentangan gagasan dan kepentingan, perlu adanya seperangkat nilai bersama yang dihormati.[18] Sedangkan isu primordialisme, yakni agama dan etnik baru-baru ini terkesan menjadi alat mobilisasi politik, Pilkada DKI Jakarta 2017.
Beberapa waktu lalu ‘Aksi Bela Islam’[19] ramai menjadi topik pembahasan di berbagai media massa nasional. Aksi Bela Islam yang mempermasalahkan pernyataan kontroversial dari Basuki Tjahaja Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta, tidak hanya menjadi permasalahan satu daerah saja. Sebab pada perkembangannya Aksi Bela Islam gelombang II, III dan IV turut melibatkan peserta aksi dari berbagai daerah, termasuk peserta yang berdatangan dari luar Pulau Jawa. Tidaklah berlebihan kalau dikhawatirkan Aksi Bela Islam yang terpusat di DKI Jakarta rawan memicu konflik berlandaskan SARA di wilayah lain.
Sebenarnya Aksi Bela Islam bisa saja menjadi sebuah gambaran yang baik sebagai kemampuan masyarakat sipil dalam menyuarakan pendapat dan pandangannya dalam rezim yang demokratis. Namun sayangnya pengerahan massa dengan landasan pandangan keagamaan MUI menjadi terkesan kontraproduktif. Sebuah bunga rampai yang berjudul Bela Islam atau Bela Oligarki merumuskan berbagai tanggapan yang secara umum mengaitkan antara analisa kelas dengan motivasi mobilisasi tersebut. Secara garis besar penulis Bela Islam atau Bela Oligarki menyayangkan mobilisasi massa begitu mudah dilaksanakan, bahkan hingga empat gelombang, atas nama penistaan agama, namun tidak dengan kelaliman kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat kelas menengah ke bawah.[20] Secara jelas pula aksi gelombang keempat pada 11 Februari 2017 lalu berubah dari yang sebelumnya menuntut penegakan hukum menjadi “tolak pemimpin kafir”. Apakah anak Indonesia tidak dapat bercita-cita menjadi Walikota/Bupati, Gubernur, Presiden, tanpa mengkhawatirkan label kafir dari massa aksi mendatang?
Menurut Wirutomo, Indonesia adalah proyek yang belum selesai, sehingga untuk melanjutkan proyek ini, perlu secara intensif membicarakan struktur, proses sosial, perubahan sosial serta fenomena sosiologis yang berkaitan seperti globalisasi dan berbagai relasi sosial.[21] Wirutomo membuat poin yang sangat baik untuk terus didiskusikan bahwa integrasi bangsa yang beragam dengan integrasi bangsa yang seragam perlu dengan ketat diperhatikan. Sebab keseragaman akan mengakibatkan integrasi koersif, seperti yang terjadi pada orde baru, sedangkan keberagaman membutuhkan integrasi fungsional. Yakni dengan melakukan pemerataan kesejahteraan dan utamanya kesadaran berbangsa.[22]
Uncivil Society atau Bad Civil Society memang menjadi massa cair yang siap untuk diberikan komando sesuai pemimpin gerakan, bahkan Wirutomo telah menuliskan solidaritas agama yang menyalahgunakan demokrasi berpotensi menjadi agresivitas massal yang anarkis. Bahkan mengarah pada civil disobedience, yakni ketidakpedulian pada segala peraturan yang ada.[23] Namun negara tetap harus mempertahankan konsolidasi demokrasi sebelum potensi tersebut benar menjadi nyata.
Menurut Rogers Brubaker, etnik bukanlah rintangan utama dan bukan pula komponen utama dalam usaha mencapai pemahaman sebangsa. Nationalising state merupakan komponen yang rumit dari kehadiran negara dalam membentuk integrasi pasar, birokrasi, sistem pendidikan, transportasi, jaringan informasi, militer, dan lain sebagainya. Komponen rumit tersebut perlu untuk membangun pemahaman ‘trans-etnik’ atau ‘supra-etnik’ dengan mendorong perlakuan yang lebih universal, seperti penegakan hukum, pemerataan kesejahteraan, pemenuhan HAM dan anti diskriminasi.[24]
Promosi kebangsaan idealnya memang tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, dan sudah sepatutnya negara mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk turut mempromosikan persatuan bangsa. Nationalising state harus secara berulang dan konsisten dilakukan ke berbagai lapisan masyarakat. Model keterlibatan masyarakat dapat berupa dukungan pemerintah terhadap berbagai gerakan sosial ataupun komoditas ekonomi yang secara konsisten dan fokus mengulas nilai integrasi dan nasionalisme.
Indonesia tidak kekurangan pengalaman dan rekam sejarah mengenai usaha mencapai pemahaman sebangsa (nationalising state). Sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan integrasi dan konsolidasi demokrasi tidak menggunakan pola koersif, termasuk pada kelompok yang ingin ‘membajak’ demokrasi sekalipun. Ancaman terhadap konflik horizontal yang diantisipasi dengan menekan pertumbuhan civil society bukanlah langkah yang tepat, sebab pertentangan gagasan dan kepentingan merupakan kondisi alami dalam demokrasi. Penggunaan SARA sebagai alat mobilisasi politik, baik disengaja maupun tidak disengaja, merupakan sebuah bentuk pengulangan yang telah terjadi sejak Indonesia merdeka, awal transisi era reformasi dan yang terjadi baru-baru ini. Karenanya uncivil society dan bad civil society penting untuk dikaji lebih lanjut dan diantisipasi ancamannya dalam dinamika integrasi kebangsaan Indonesia.
[1] Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, (New York, United States of America: Verso, 2000), hal.121
[2] Kementerian PPN/Bappenas, Laporan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Strategi Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa,http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kajian%20Tahun%202015/Stranas/Final%20Laporan%20Stranas%202015.pdf, (diunduh pada 9 Februari 2017)
[3] Paulus Wirutomo, “Integrasi Sosial Masyarakat Indonesia: Teori dan Konsep” dalam Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 2012), hal.35
[4] Ibid, hal.5
[5] Lucia Ratih Kusumadewi: “Relasi Sosial Antar kelompok Agama” dalam Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 2012), hal.147
[6] Felix Heiduk, “Between A Rock and A Hard Place: Radical Islam in Post-Suharto Indonesia”, IJCV: Vol. 6 (1) 2012, pp. 26-40, hal.30
[7] Lucia Ratih Kusumadewi, Op Cit, hal.150
[8] Gerry van Klinken, Communal Violence and Democratization in Indonesia, (New York: Routledge, 2007), hal.18
[9] Ibid, hal.19-21
[10] Robert W. Hefner, Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization (New Jersey: Princeton University Press, 2005), hal.278-279
[11] Ibid, hal.280
[12] Lihat Ibid, hal.284 dan Simone Chambers dan Jeffrey Kopstein, “Bad Civil Society” di dalam Political Theory, Vol.29, No.6 (Dec., 2001), pp.837-865, hal.838-839
[13] Robert W. Hefner, Op Cit, hal.285-286
[14] Mark Woodward et. al, “The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia” dalam Cont Islam (2014) 8:153-171, hal.154
[15] Ibid, hal.169
[16] Andi Rahman Alamsyah, “Civil Society dan Integrasi dalam Konteks Demokrasi” dalam Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 2012), hal.281
[17] Selengkapnya lihat Simone Chambers dan Jeffrey Kopstein, Op Cit,
[18] Chantal Mouffe, Op Cit, hal.121
[19] “Aksi Bela Islam” merujuk pada gerakan kelompok masyarakat beragama Islam yang menuntut agar pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Seribu (27 September 2016) yang dinilai menistakan agama Islam dan menghina Ulama untuk diproses secara hukum. Terdapat empat gelombang Aksi Bela Islam, yakni: (I) tanggal 14 Oktober 2016, (II) tanggal 4 November 2016, (III) tanggal 2 Desember 2016 dan (IV) tanggal 11 Februari 2017.
[20] Dede Mulyanto dan Coen Husein Pontoh (ed), Bela Islam atau Bela Oligarki?: Pertalian Agama, Politik dan Kapitalisme di Indonesia, (Pustaka IndoPROGRESS dan Islam Bergerak, 2017), dapat diunduh pada https://www.dropbox.com/s/k7appn77mmhaltpt/Aksi_Bela_Islam-IP-IB.pdf?dl=1&pv=1
[21] Paulus Wirutomo, Op Cit, hal.8
[22] Paulus Wirutomo, Op Cit, hal.289
[23] Ibid, hal.315
[24] Rogers Brubaker, “Nationalising States in the Old ‘New Europe’ – and the New”, hal.413-414